 Malam itu, Erwin (34) menatap lekat-lekat pemandangan di hadapannya. Kedua putranya, Ilham (5) dan Rabel (3) nampak lahap memasukan suap demi suap makanan ke mulut mungil mereka. Tak jauh, Mesra (25) istrinya, sedang menyuapi si bungsu, Imam (2) yang belum bisa makan sendiri. Sekilas ia melirik perut istrinya yang nampak semakin membesar. Tak sampai satu bulan lagi mungkin tiba waktunya untuk melahirkan. Mata Erwin berkaca-kaca, sejuta pikiran berkecamuk di kepalanya. Dadanya sesak seolah ada batu besar menghimpitnya.
Malam itu, Erwin (34) menatap lekat-lekat pemandangan di hadapannya. Kedua putranya, Ilham (5) dan Rabel (3) nampak lahap memasukan suap demi suap makanan ke mulut mungil mereka. Tak jauh, Mesra (25) istrinya, sedang menyuapi si bungsu, Imam (2) yang belum bisa makan sendiri. Sekilas ia melirik perut istrinya yang nampak semakin membesar. Tak sampai satu bulan lagi mungkin tiba waktunya untuk melahirkan. Mata Erwin berkaca-kaca, sejuta pikiran berkecamuk di kepalanya. Dadanya sesak seolah ada batu besar menghimpitnya.
Ini, adalah makan malam terakhir …
Barangkali, itulah ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan betapa pahitnya keputusan yang diambil oleh Erwin Kurniawan (34) atas nasib keluarganya. Sebab keesokan harinya, warga Telaga Sam-sam, Kandis-Siak, Riau menemukan Erwin beserta ketiga anak dan istrinya plus bayi yang sedang dikandung istrinya, telah meninggal dunia. Media (9/6) memberitakan, kematian Erwin sekeluarga diduga kuat merupakan tindakan bunuh diri, dengan cara membubuhi racun saat makan malam. Setelah disholatkan di Masjid As-salam, Erwin dimakamkan dalam satu lubang bersama kedua anak tertuanya, sedangkan sang istri bersama anak bungsunya di liang lahat yang lain.
Erwin tidak sendiri. Masih lekat di benak kita, beberapa waktu yang lalu di Koja Jakarta Utara (14/12/04), Galang Ramadhan (6) akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah sempat sehari dirawat di RSCM. Luka bakar luar biasa membuatnya tak mampu bertahan. Galang menyusul kematian adiknya Galuh (4) yang meninggal di tempat setelah ibunya Jasih (30) frustasi membakar diri berikut Galang dan adiknya, saat Mahfud (32) sang ayah sedang bekerja menjadi kuli panggul di pelabuhan Tanjung Priok.
Yang terbaru, seperti dimuat oleh Suara Merdeka (19/06), adalah kisah tragis bunuh diri a la Romeo and Juliet –menenggak racun-- yang dilakukan Budi Harjo (23) dan Novalina (18) di Klaten, Jawa Tengah.
Kisah getir Erwin dan Jasih, juga Budi dan Novalina, adalah sedikit saja contoh dari kian tingginya angka bunuh diri di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Ketidakmampuan negeri kita, tak kunjung bangkit dari keterpurukan, dengan indikasi negara mampu menciptakan kesejahteraan dan menjamin penghidupan yang layak bagi warganya, membawa implikasi buruk bagi rakyat kelas menengah ke bawah. Kelompok masyarakat yang paling rentan, dan potensial menjadi penyumbang tertinggi angka bunuh diri.
Sulit untuk mencari data statistik pasti tentang bunuh diri, namun bila kita telusuri publikasi tentang hal ini dari berbagai sumber maka kita akan mendapatkan data mencengangkan. Di Jakarta misalnya, sebagai barometer, hanya ada 19 kasus bunuh diri pada tahun 2002. Lalu melonjak hingga 62 kasus atau tiga kali lipat pada tahun 2003. Tahun 2004, hingga pertengahan Juni saja jumlahnya sudah 38 kasus. Maka tidak heran jika di tahun 2006, secara nasional, sudah ada 114 kasus bunuh diri yang terdeteksi media.
Dari data tersebut, latar belakang profesi pelaku bunuh diri diantaranya adalah pelajar, karyawan perusahaan, pembantu rumah tangga, buruh, dan kebanyakan pengangguran. Ini menegaskan bahwa rentang usia pelaku adalah masa-masa produktif (20-50 tahun), dan dari lapisan yang mengalami kesulitan yang sama yaitu beratnya mempertahankan hidup akibat tekanan ekonomi. Khusus pada pelaku yang telah berkeluarga, banyak diantaranya yang bahkan mengikutsertakan anak-anaknya menuju kematian.
Tingginya angka bunuh diri, dan juga semakin banyaknya jumlah anak-anak bergizi buruk (kelaparan) di seantero wilayah negeri ini, menunjukkan fakta realita dengan data yang dikemukakan Presiden SBY --angka kemiskinan turun menjadi 16 % di tahun 2005 dari 23,4 % di tahun 1999, juga pengangguran yang berkurang menjadi 10,4 % saja pada Februari 2006--, menjadi tidak sinkron.
Kekeliruan cara hitung pemerintah dalam memetakan kondisi rakyat jelata ini melahirkan kebijakan yang tak ramah rakyat. Beras mahal, minyak goreng mahal, transportasi mahal, pendidikan mahal. Segalanya terasa susah dan berat bagi rakyat. Belum lagi, kultur tolong-menolong yang mulai memudar sebab untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja sudah sulit. Kondisi ini menciptakan kesuraman dan melahirkan depresi, sebagai pencetus awal niatan bunuh diri.
Dan depresi-depresi baru di Jawa Tengah prediksinya juga akan terus bermunculan. Sebab, RAPBD Jateng 2008 hanya menganggarkan 0,48% dari total APBD untuk menuntaskan pengangguran. Padahal jumlah pengangguran terus merangkak naik menjadi hampir 1, 5 juta orang di tahun 2007 dari 1,2 juta di tahun 2006. Itu artinya, pemerintah tidak terlalu antusias untuk menolong rakyatnya. Tiga perempat anggaran dihabiskan hanya untuk belanja rutin pegawai.
Mengenali Diri
Bunuh diri adalah problematika multidimensional. Ia tak bisa dilihat hanya dari sudut tindakan kriminalitas (hukum) saja. Memasukkan pelaku bunuh diri (yang gagal mati) ke penjara, bukan solusi akhir. Sebab bunuh diri lahir dari buruknya kondisi diri dan lingkungan yang melingkupi ranah sosial, ekonomi, pendidikan, relijiusitas bahkan juga politik (kebijakan publik).
Bunuh diri adalah persoalan khas kemanusiaan. Dibanding makhluk hidup lain, boleh dikata hanya manusia yang mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, dari sekian kompleks faktor eksternal, semuanya mengarah kepada satu hal penting, yaitu kemampuan mengenali dirinya sendiri. Dalam bahasa penemu Multiple Intellegence (Multikecerdasan), Dr. Howard Gardner, itu disebut dengan kecerdasan intrapersonal.
Mengenali diri sendiri (intrapersonal), sebagai pribadi dan karakteristik kemanusiaan adalah persoalan seberapa luas wawasan kita dalam mengenal sifat-sifat jasad, emosi, dan spiritual diri. Keluasan wawasan ini menjadi penting, sebab ia menjadi satu-satunya tumpuan harapan saat tiba-tiba diri menghadapi sesuatu yang disebut dengan : kesedihan, keputusasaan, kekecewaan, kegetiran, kepahitan, dan keserbamalangan. Mampukah kita bertahan, itulah pertanyaan intinya.
Pada dasarnya, manusia lulus -dengan catatan- uji kelayakan dari malaikat, karena manusia menyimpan potensi dualisme kepribadian, ketaatan dan kesesatan, dibalik keunggulan akal budinya.
Manusia, selain diciptakan dalam keseimbangan dan kesempurnaan (QS. 95:4), juga diberikan unsur kelemahan (QS. 4: 28), terlihat dari tanah liat dan lumpur sebagai bahan dasar pembentuk (QS. 15:26) sebelum ditiupkan ruh kehidupan kepadanya (QS. 15:29)
Artinya, manusia adalah sebuah totalitas yang sarat dengan energi, yang disusun secara spesifik dan unik. Ia memiliki watak transedental yang ingin mencapai kesempurnaan, ditengah watak material yang lemah dalam menghadapi berbagai hambatan kosmis.
Karena itu, kelemahan dan ketidakberdayaan menjadi sifat alami manusia. Manusia penuh dengan keluh kesah dikala susah dan kikir dikala suka (QS. 70: 19-22). Konsekuensinya, manusia membutuhkan pola hidup bersama dan kebutuhan pertolongan dari kekuatan diluar dirinya. Dari kaca mata positif, kesadaran atas kelemahan diri ini patut disyukuri sebab itu menegaskan manusia sebagai hambanya Allah Sang Pencipta.
Jadi, bisa dipastikan, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang terbebas dari masalah dan ujian kehidupan. Namun bisa dipastikan pula, bahwa setiap ujian hidup itu pasti menemukan penyelesaiannya. Masalah adalah hal biasa, yang menjadi luar biasa, dan menjadi tolok ukur kebesaran jiwa, adalah soal bagaimana pilihan metode kita memecahkan dan bergelut dengan masalah. Pahlawan dan pecundang, dua luaran yang berbeda, berasal dari satu masalah yang sama. Dan dunia cuma diisi oleh dua tipe manusia itu saja sebenarnya.
Dr. Qaidh Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan atau yang diterjemahkan menjadi Jangan Bersedih, berkesimpulan bahwa terpaku pada waktu yang terbatas dan kondisi kelam hanya akan menghasilkan perasaan kesusahan, kesengsaraan, dan keputusasaan dalam hidup. Terutama bila terpaku menatap dinding-dinding kamar dan pintu-pintu yang sempit. Hal baru akan didapatkan saat kita menembuskan pandangan sampai ke belakang tabir dan berpikir lebih jauh tentang hal-hal yang berada di luar pagar ruangan.
’Luar pagar ruangan’ adalah optimisme. Kita tidak sendiri. Pipi yang setiap malam basah karena tangis derita tak terhitung banyaknya di sekitar kita. Kehilangan, keterbatasan dan ketidakmampuan juga bertebaran dimana-mana, silih berganti dari detik ke detik. Namun, dunia tetaplah penuh dengan cerita orang-orang yang gigih mempertahankan hidup. Jika kita cermat, kegigihan ditengah keterbatasan itu adalah guru kehidupan yang tak ternilai harganya.
Bunuh diri identik dengan keputusaasaan. Padahal jika kita mau bersabar sedetik lagi saja saat putus ada maka secercah harapan akan datang. Khalifah Ali telah berulang kali mengalaminya, menurut beliau, saat yang paling dekat dengan jalan keluar adalah ketika telah terbentur pada putus asa. Luar biasa !
Obat derita tidak hanya ditemukan di dunia saja. Hampir setiap ajaran agama, Islam setidaknya, memberi jaminan bagi umatnya --semacam pelipur lara--, bahwa penderitan di dunia adalah tiket menuju kebahagiaan abadi di akhirat, dengan catatan, selama kita ikhlas dan sabar menghadapi ujian kehidupan itu.
Kant, filsuf Jerman, bahkan turut pula meyakininya. Menurut Kant, sesungguhnya kehidupan di dunia ini belum lagi sempurna, pasti ada panggung kedua. Sebab, kita semua melihat di sini, orang yang zalim dan dizalimi, namun kita tak mendapatkan keadilan. Orang yang menang dan yang kalah, namun kita tak mendapatkan balasan yang pasti. Maka, pasti ada alam lain yang akan menyempurnakan keadilan.
Katup Pengaman
Bunuh diri tidaklah sederhana. Sebab, pelakunya sekaligus menjadi korban. Ia adalah kasus kompleks. Bahkan bisa juga menjadi gunung es dari kekuatan sebuah bangsa. Bunuh diri, paling tidak telah menyeret dua komunitas penting yang menjadi pilar sebuah bangsa, yaitu keluarga dan komunitas sosial (kemasyarakatan), sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Keluarga, sebagai katup pengaman pertama –meminjam istilah Imam B. Prasojo—sejatinya adalah tempat pertama dan paling utama untuk berkeluh kesah dan saling bahu membahu mengatasi persoalan sekecil apapun itu. Kedekatan emosional dan historikal, apalagi genetikal, adalah faktor penting yang membuat seseorang merasa berharga dan termotivasi untuk terus hidup.
Sementara komunitas sosial seperti RT/RW, kampung, dan desa adalah katup pengaman kedua, saat permasalahan ditingkatan keluarga mulai membutuhkan uluran tangan dan kepedulian tetangga atau kerabat sekitar. Kepedulian dan pengakuan sosial menjadi sangat berarti saat keluarga tak lagi mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Masalahnya, sekarang ini, kedua katup pengaman itu nampak kehilangan gigi. Keluarga tak lagi menjadi tempat yang paling dirindu, dan masyarakat pun mulai tak acuh, terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. Kondisi sulit membuat orang ’terpaksa’ berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri ketimbang mengulurkan tangannya kepada orang lain.
Di titik kritis inilah, pemerintah atau negara dapat berperan. Yaitu dengan merancang program sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan komunitas sosial. Kebijakan memahalkan harga kebutuhan-kebutuhan dasar bukanlah program yang ramah keluarga. Sebab, semua anggota keluarga pada akhirnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi jasadiyah untuk bertahan hidup namun di satu sisi lain kehilangan kehangatan emosi dan spiritual khas keluarga, yang pada gilirannya tinggal menyisakan kerentanan. []
Edited Version dimuat di Suara Merdeka (Selasa, 3 Juli 2007)




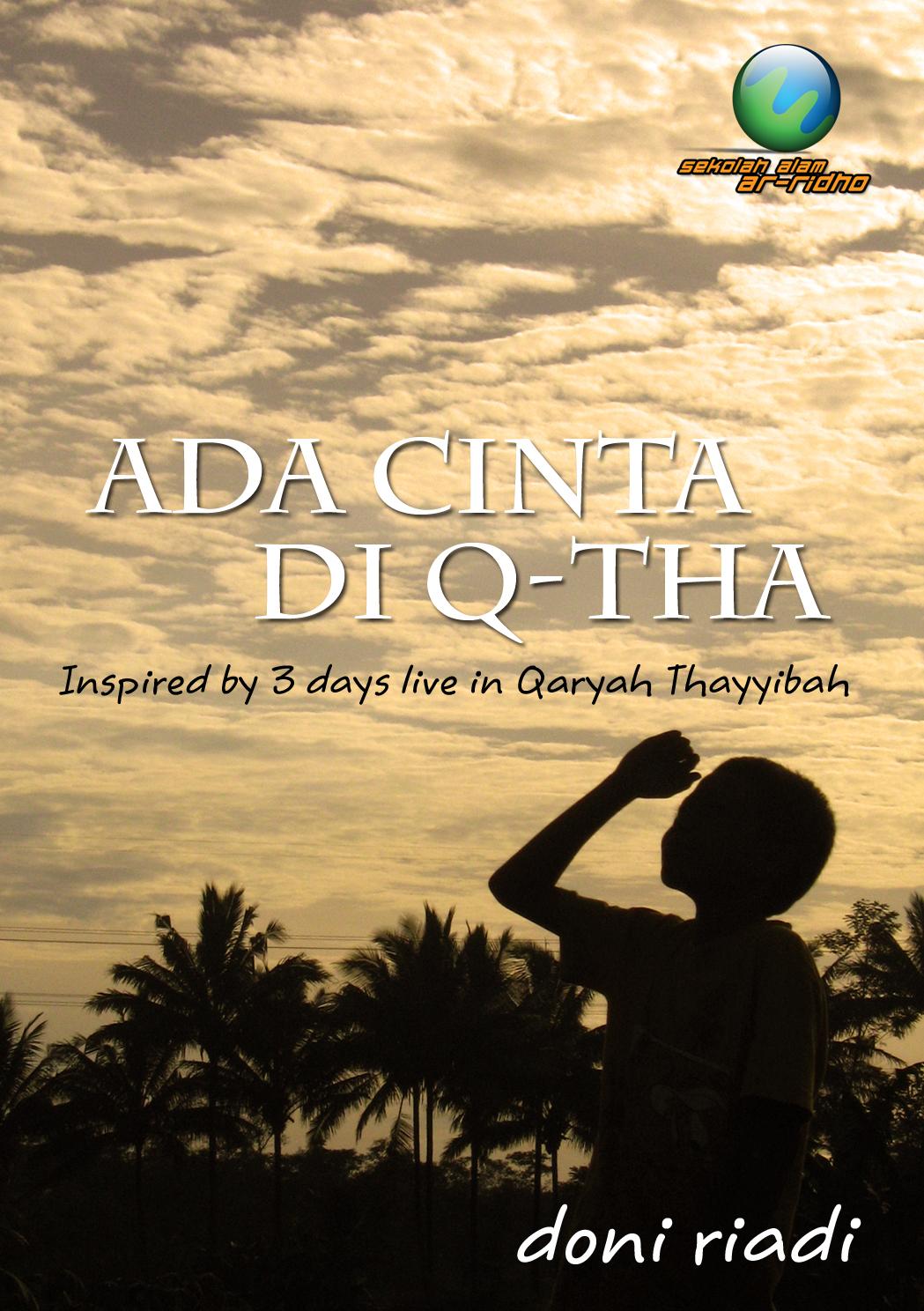
0 komentar